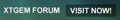

Sebut saja namanya Pletho. Remaja berusia kurang lebih 16 tahun ini berkeliaran di jalanan, bersama sekitar 24 orang temannya tinggal dan mencari nafkah di sekitar Jl. Mangkubumi hingga perempatan Tugu Yogyakarta. Julukan untuk mereka cukup eksotis, dalam rangka menaikkan derajat kita sebagai manusia normal, serta memarjinalkan mereka, lantas kita menyebut mereka “anak jalanan.” Anak-anak yang tinggal di jalanan. Konon mereka tidak menjadi manusia karena tinggal di jalanan, sedangkan kita yang punya standar hidup (yang kita anggap normal) sesuai jaman sekarang mengganggap diri kita berhasil menjadi manusia.
Memang parameter untuk menjadi manusia itu seperti apa sih? Jika dinilai secara kasat mata, asalkan dia berkaki dua dan berjalan tegak dan berpakaian bukankah itu manusia? Anak-anak kurang beruntung yang berkeliaran di seputaran Tugu Jogja itupun adalah manusia. Tapi pernahkah kita menilai mereka sebagai manusia? Saat kita memburu eksotisme Jogja dengan berfoto di tugu, pernahkan kita memperhatikan mereka sebagai manusia?
Kemudian saya teringat piramida kebutuhan Abraham Maslow, maka parameter menjadi manusia adalah puncak tertinggi piramida itu yakni kebutuhan aktualisasi diri, berbeda dengan binatang yang kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan diri adalah dengan makan dan kawin saja. Dan mendadak gaya hidup modern adalah kebutuhan aktualisasi diri tersebut. Semua orang mengejar kehidupan modern agar dianggap hidup normal. Semua orang mengaktualisasi dirinya modern dengan mengejar setiap trend kehidupan modern. Kelas atas menggunakan aktualisasi diri modern itu untuk melanggengkan posisinya sebagai kasta tertinggi, kelas menengah mengejar aktualisasi diri modern itu untuk berupaya menaikkan derajat menjadi kelas atas, sedangkan kelas bawah terseok-seok mencoba mengejar ketertinggalan, berusaha sekuat tenaga mengaktualisasikan diri secara modern agar dianggap sebagai manusia.
Maka Pletho dan kawan-kawan senasibnya berusaha keras agar dianggap manusia, sekalipun kehidupannya keras dan tinggal di jalanan, ia berusaha mengabaikan fakta bahwa kebutuhan dasarnya sebagai manusia untuk memiliki sandang, pangan, papan, belum terpenuhi. Karena Pletho ingin menjadi manusia, ia harus mengikuti standar modernisasi agar menjadi manusia, maka ditengah kesibukannya mengejar manusia lain dengan gitar kencrung mengharap recehan, atau beberapa rekannya akan menadah gelas bekas mie instan di lampu merah, mereka akan menghabiskan uang tersebut untuk menuju warnet dan mengakses Facebook dan Twitter. Ya, karena Facebook mereka anggap satu-satunya cara agar mereka juga dapat mencicipi standar hidup modern manusia.
Mengakses Facebook 5 jam sehari menjadi biasa bagi mereka, jatah makan terpaksa disunat sedikit untuk mengakses situs Mark Zuckerberg tersebut. Dalam benak Pletho dan kawan-kawan tentu tersirat “aku tak punya rumah tinggal, lalu untuk apa kuhabiskan waktuku di Facebook? Ah, tapi inilah cara agar aku menjadi manusia seperti yang lain.” Selain menghabiskan waktu di Facebook, rata-rata anak-anak yang tinggal di Jl. Mangkubumi ini memiliki telepon genggam. Tanpa henti mereka memencet tutsnya untuk sms-an atau malah menelpon rekannya yang berada di tempat lain. Mereka juga akan membelanjakan uangnya di minimarket biru atau merah, sekadar membeli air mineral atau rokok (dengan tatapan sinis penjaga minimarket yang barangkali berpikir aduh bajunya kucel anaknya kotor, ngapain masuk kesini). Karena manusia modern gemar membelanjakan uangnya juga di minimarket yang lebih bersih dan elegan ketimbang warung sederhana milik tetangga.
Inilah kejanggalan menjadi manusia, kita yang lebih beruntung memiliki rumah tinggal dan tak pusing memikirkan bagaimana makan siang lantas mengurung diri kita dalam kungkungan modernisasi (hayoh siapa yang tak memiliki Facebook, Twitter dan telepon genggam? Apakah anda menganggap menguasai teknologi itu? Atau teknologi itu yang menguasai anda?). celakanya kita lantas menjadikan kungkungan modernisasi itu sebagai standar hidup menjadi manusia. Dan anak jalanan yang kemanusiaannya sudah diabaikan dengan terpaksa tinggal dijalanan, akhirnya terseok-seok berupaya menjadi manusia dengan menghabiskan uangnya di warnet-warnet untuk sekedar memberi jempol “like” pada status teman Facebooknya, teman yang barangkali tak benar-benar dikenalnya. Mereka harus melupakan fakta bahwa mereka tak punya rumah, harus berantem dengan kelompok anak jalanan lain untuk berebut wilayah, harus lari tiap Satpol PP datang menangkap (dengan alasan pembinaan). Harus meminta uang pada orang asing untuk dapat membeli makanan, harus ngelem agar mabuk dan melupakan realita.
Tapi kemudian saya berpikir, jangan-jangan Pletho dan kawan-kawan anak jalanan sadar bahwa mereka dilupakan masyarakat modern? Maka mereka Facebook-an dan bertelepon genggam ria untuk melupakan fakta bahwa mereka manusia terlupakan. Itu adalah penghiburan diri, benteng terakhir mereka menghadapi kerasnya hidup di jalanan. Renungan panjang ini membuat saya mengernyit jengah, betapa menyedihkannya menjadi manusia modern. Yang berkecukupan Facebook-an dan Twitter-an untuk bersenang-senang dan melupakan kelas dibawahnya, sedangkan kelas bawah Facebook-an dan Twitter-an untuk berusaha menaikkan kelas, dan melupakan fakta bahwa mereka dilupakan dan tak dianggap manusia.
Yogyakarta, 9 februari 2012.
Aris Setyawan: Penulis adalah mahasiswa jurusan Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang bosan dengan setiap hari perkuliahan. Bermain drum untuk Aurette and the Polska Seeking Carnival, penggila kucing, penggiat peduli anak jalanan di Save Street Child Jogja, kutu buku poll-poll-an, berharap semoga satu hari Radiohead konser di Indonesia
http://m.kompasiana.com/post/sosbud/2013/02/09/menjadi-manusia/
Menjadi Manusia
Oleh: Aris Setyawan | 09 February 2013 | 00:59 WIB.